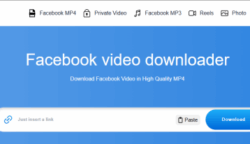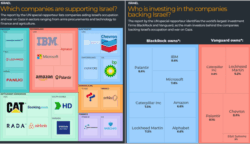QRIS Kurang Diminati di Aceh, Masyarakat Lebih Suka Transaksi Tunai
Oleh: Teuku Farhan*
Event nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 yang berlangsung di Aceh pada bulan September 2024 memberikan dampak cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor perbankan.
Namun, di tengah semangat mendorong digitalisasi transaksi, data menunjukkan bahwa masyarakat Aceh dan peserta PON masih lebih nyaman menggunakan uang tunai dibandingkan dengan metode pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pada periode PON, tercatat transaksi tunai melalui ATM dan Teller bank mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp 8,66 triliun. Sementara itu, transaksi non-tunai melalui QRIS hanya mencapai Rp 65,58 miliar.
Angka ini jauh lebih kecil, dan memberikan sinyal bahwa masyarakat Aceh masih belum siap sepenuhnya untuk beralih ke transaksi digital, terutama di sektor ritel dan usaha kecil. Dan kehadiran ATM masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Kita patut apresiasi langkah perbankan di Aceh yang menambah jumlah ATM di lokasi strategis dan nominal uang pecahan kecil sehingga memudahkan warga, tanpa antri dan transaksi tunai yang lancar.
Berbeda dengan daerah lain yang justru jumlah ATM-nya dikurangi. Itulah Aceh. Aceh itu selalu tampil beda dan istimewa. Perlu perlakuan khusus.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah digitalisasi transaksi benar-benar relevan untuk diterapkan secara masif di Aceh yang masih tergolong minim industri?
Di saat kota-kota besar di Indonesia mulai berlomba mendorong penggunaan QRIS dan pembayaran digital, realitas di Aceh justru menunjukkan arah yang berbeda.
Eksploitasi Digitalisasi Transaksi untuk UMKM
Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar dorongan besar dari perbankan untuk mengadopsi transaksi digital, dengan alasan hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan transaksi.
Salah satu sektor yang paling terkena imbas dorongan ini adalah UMKM, termasuk usaha kecil seperti toko kelontong dan warung-warung tradisional. Bank dan penyedia layanan pembayaran digital sering kali berargumen bahwa menggunakan QRIS akan membantu usaha kecil beradaptasi dengan zaman.